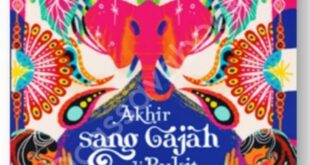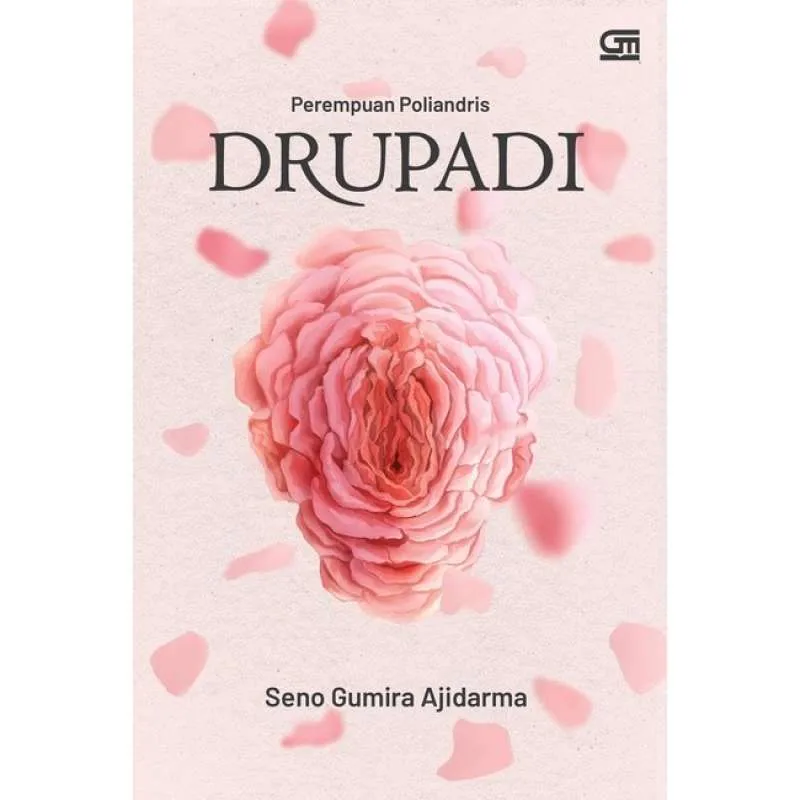
Nama Drupadi dalam benak saya seperti memanggil sejenis kesedihan yang anggun. Ketika membaca judul novel karya Seno Gumira Ajidarma: Drupadi Perempuan Poliandris, ingatan saya memilih singgah lebih dulu ke panggung pedalangan, ke suara dalang yang lirih mengiringi langkahnya yang lembut. Di sana, Drupadi adalah lambang ketabahan perempuan: selalu setia dan diam di tengah badai takdir yang ditentukan oleh laki-laki. Dalam Mahabharata klasik, ia dipuja sekaligus direnggut, sehingga menjadi simbol kehormatan yang diperjualbelikan dalam permainan kuasa.
Ketika berjumpa dengan narasi-narasi Seno Gumira Ajidarma (SGA) dalam novel ini, yang seolah menghadirkan panggung untuk Drupadi seorang sendiri, saya merasa dijatuhkan dari menara nostalgia. Drupadi hadir sebagai sosok yang menggugat sejarah, menatap pembaca dari celah luka, dan tubuh yang jadi medan perebutan. Drupadi juga diberi kekuatan serta keberanian untuk mengambil alih cerita.
Pada suatu titik dalam sejarah kesusastraan Indonesia, seorang pengarang merasa perlu menegaskan bahwa Drupadi tidak pernah dinodai. Bukan karena hendak memutarbalikkan cerita, pasalnya, di dalam teks Mahabharata yang sudah bertahun-tahun dilanggengkan itu, tubuh perempuan seringkali menjadi arena pelampiasan kuasa, harga diri lelaki, dan kesewenang-wenangan moral yang tunggal. Maka SGA, dalam novelnya Drupadi, menolak satu adegan paling dramatis dan paling diingat dalam pewayangan: ketika kain Drupadi tak habis-habisnya ditarik oleh Dursasana. Ini merupakan suatu keberanian seorang penulis yang menulis ulang kisah Mahabharata dengan menantang kodrat yang dianggap tak bisa digugat. SGA menulis ulang apa itu kebenaran, kesucian, dan siapa yang berhak menentukannya.
Penulis yang mengisi sebuah kolom di Majalah Mingguan Zaman sepanjang tahun 1983-1984 itu, dengan segala kesadaran literernya, telah mendekati dunia wayang bukan sebagai warisan yang harus dibonsai dan disakralkan. Dunia Wayang baginya adalah ruang tafsir yang hidup dan dapat dinegosiasi. Ia tidak sedang membuat ulang Mahabharata menjadi novel. Ia sedang mempertanyakan alasan kisah Mahabharata tetap seperti itu, dan alasan perempuan seperti Drupadi harus terus menanggung luka yang dikarang oleh sistem nilai patriarkal. Maka dalam novel itu, Drupadi tampil sebagai tokoh yang menuntut hak asasinya. Ia menjadi simbol kesetiaan lima suami, menjadi perempuan poliandri—sebuah keberanian naratif yang mengubah cara kita membaca ulang epos, dengan rasa keberanian untuk bertanya.
Salah satu kekuatan utama dalam novel Drupadi karya SGA adalah penggunaan monolog dramatik sebagai cara bercerita. SGA memberi ruang sepenuhnya kepada tokoh Drupadi untuk menyuarakan isi hatinya tanpa interupsi, tanpa narator yang mengarahkan, dan tanpa bimbingan moral dari luar. Strategi ini menyajikan kemarahan Drupadi sebagai ledakan emosional sekaligus sebagai gugatan yang sangat terstruktur terhadap sistem nilai yang menindas perempuan. Dengan mengandalkan monolog dramatik, SGA menciptakan narasi yang intim dan teatrikal.
Monolog dramatik ini dihidupkan dengan gaya retoris yang kuat. SGA menempatkan Drupadi dalam posisi orator: ia berbicara kepada para Pandawa, tetapi juga seolah berbicara kepada pembaca, kepada sejarah, dan kepada masyarakat patriarkal secara luas. Gaya retoris yang dibawakan mencakup pertanyaan-pertanyaan tajam (“Apakah kalian sudah lupa?”, “Apakah aku tidak berarti apa-apa?”), pengulangan frasa untuk menegaskan luka (“Aku Drupadi… Aku Drupadi…”) serta kontradiksi yang mengguncang moral tradisional (“Bukankah pria dan wanita setara?”). Retorika semacam ini menjadi sarana efektif untuk menyeret pembaca masuk ke dalam ruang balairung batin Drupadi dan mengaduk-aduk kesadaran mereka.
Cara bercerita semacam ini juga bekerja sebagai cara untuk membongkar mitos. Dalam versi-versi Mahabharata yang lebih konvensional, penderitaan Drupadi memang diakui, namun seringkali diserap ke dalam narasi heroisme laki-laki. SGA justru menggeser pusat narasi ke arah tubuh dan pengalaman perempuan. Dalam monolog ini, Drupadi menelanjangi kelemahan Pandawa, mengungkap kebungkaman mereka sebagai bentuk pengkhianatan. Drupadi juga menggunakannya sebagai senjata retoris untuk mendekonstruksi keagungan para “ksatria” dan menggugat moralitas ganda yang melekat dalam sistem patriarki.
Lebih dari itu, penggunaan monolog dramatik memperlihatkan keberanian SGA dalam mengeksplorasi bentuk. Strategi ini juga mengandung potensi retoris yang politis, karena memberi pengalaman langsung kepada pembaca untuk “mendengar” perempuan yang marah, bukan melalui tafsir tokoh lain, melainkan dari dalam kesadarannya sendiri. Monolog dramatik menjelma menjadi site of resistance, ketika bahasa mampu mengungkap trauma sekaligus mengklaim otoritas wacana.
SGA membiarkan karakter menghidupi peristiwanya melalui suara. Teknik yang mendekatkan narasi pada bentuk teater; sebuah “panggung kata” di mana konflik batin, sejarah kekerasan, dan kritik sosial berpadu dalam satu ruang bicara. Dengan demikian, monolog dramatik dalam Drupadi merupakan strategi etis dan politis, yaitu suatu upaya memberi tempat dan hak bicara penuh kepada tokoh perempuan untuk menuntut keadilan.
Strategi monolog dramatik dalam novel ini juga dapat dibaca sebagai cara untuk menata ulang posisi gender dalam narasi, sekaligus sebagai bingkai untuk menghadirkan maskulinitas simbolik dalam tubuh tokoh perempuan. Lewat monolognya yang lantang dan menggelegar, Drupadi tampil sebagai subjek aktif yang menuntut, menyerang, dan mendobrak kebungkaman. Monolog menjadi medan bagi Drupadi untuk mengambil alih bahasa kuasa, yang dalam budaya patriarkal selama ini identik dengan peran laki-laki.
“Kemarahan adalah hak manusia, dan seorang ksatria tidak boleh melupakan kewajibannya. Para Pandawa merasa dirinya suci dengan menahan kemarahannya menjadi kesabaran semu. Itu suatu pengingkaran terhadap kehidupan. Kita mempunyai hak untuk suatu kemarahan yang beralasan, dan aku menggunakan hak seorang perempuan.” (Ajidarma, 2017)
Kutipan monolog tersebut menyingkap pergulatan batin Drupadi secara intens. Ia tidak lagi menjadi tokoh pasif dalam epik Mahabharata, tetapi menjadi subjek yang sadar akan hak dan posisinya, terutama sebagai perempuan dalam struktur patriarki dan sistem nilai ksatria. Kalimat “aku menggunakan hak seorang perempuan” menjadi klimaks dari subjektivitas yang diaktifkan secara kritis.
Drupadi melalui kutipan tersebut menyampaikan argumen yang rasional: “Kemarahan adalah hak manusia” dan “kita mempunyai hak untuk suatu kemarahan yang beralasan”. Sebentuk retorika dramatik yang mencampurkan logos (nalar) dan pathos (emosi). Ia menyuarakan protes yang beralasan, bukan sekadar kemarahan kosong.
Monolog tersebut menyiratkan kesan dialogis meskipun hanya suara Drupadi yang terdengar. Drupadi seakan juga berbicara kepada ‘yang lain’ secara imajiner—Pandawa, masyarakat, bahkan sistem nilai yang mengekangnya. Strategi ini memperlihatkan bahwa monolog dramatik mampu menghadirkan sesuatu yang konfrontatif, menjadi arena kritik terhadap ideologi dominan, dalam hal ini maskulinitas dan kehormatan palsu para Pandawa.
“Drupadi berjalan perlahan mendekati Yudhistira, gesekan kaki dan kainnya terdengar jelas menyapu lantai. Di hadapannya ia tidak bersimpuh seperti biasanya. Ia tetap berdiri. ‘Maafkanlah aku, Yudhistira, tapi kali ini aku harus bicara. Aku mengatakan yang sesungguhnya.’” (Ajidarma, 2017)
Berbeda dari monolog dramatik murni yang umumnya tampil sebagai wacana reflektif panjang dan utuh, kutipan Drupadi dalam novel SGA tersebut memperlihatkan bentuk yang lebih subtil dan menyatu dengan narasi situasional. Monolog dramatiknya muncul dalam adegan yang mengandalkan ketegangan gestural: Drupadi berjalan perlahan, gesekan kainnya menyapu lantai, dan yang paling mencolok adalah ketika Drupadi tidak bersimpuh seperti biasanya. Ia berdiri, menatap langsung ke arah Yudhistira. Ketika ia berkata, “Maafkanlah aku, Yudhistira, tapi kali ini aku harus bicara. Aku mengatakan yang sesungguhnya,” kata-katanya mengguncang sebab disiapkan oleh tubuh yang sudah lebih dulu bicara. Inilah yang disebut sebagai embedded dramatic monologue, sebuah bentuk monolog dramatik yang dibangun dari konteks, gestur, dan situasi. Strategi ini menciptakan retorika kinestetik di mana tubuh Drupadi menjadi sumber makna. Ketidaksediaannya untuk bersimpuh adalah penolakan terhadap relasi kuasa tradisional, sebuah rupture in ritual, yaitu ketika tokoh memutus pola simbolik yang selama ini mengikat dirinya.
Ucapan “kali ini aku harus bicara” menandai artikulasi kesadaran baru dan keberanian untuk melampaui diam yang dipaksakan. Di balik kalimat “aku mengatakan yang sesungguhnya”, kita mendengar gema konflik batin yang lama dipendam. Sebuah interiorization of conflict yang akhirnya meletup ke permukaan. Dalam strategi monolog dramatik, momen ini menjadi titik balik emosional dan psikologis. SGA menyusun monolog ini dengan pendekatan simultan: verbal, gestural, dan dramatik, sehingga pembacaan terhadap tokoh Drupadi adalah pembacaan sebagai perempuan yang mengambil alih kendali narasi, membongkar nilai-nilai yang selama ini membungkamnya.
SGA menyusun ruang bagi Drupadi untuk mengekspresikan rasa sakit dan amarah sekaligus mengonstruksi etos kepemimpinan, keberanian, dan bahkan agresi verbal yang selama ini dilekatkan pada karakter maskulin dengan mengambil bentuk monolog dramatik. Ia menantang Pandawa, mempertanyakan kehormatan dan integritas mereka, bahkan menyiratkan bahwa dirinya lebih ksatria daripada mereka. Drupadi tidak lagi bicara sebagai istri atau perempuan yang ditimang-timang. Ia bicara sebagai figur yang ‘memanggul kebenaran dan menuntut keadilan’. Dalam gestur ini, tampak bagaimana strategi monolog dramatik memungkinkan tubuh perempuan secara simbolik memakai “baju besi” maskulinitas untuk melawan ketidakadilan.
Monolog Drupadi juga menunjukkan bagaimana bahasa dan keberanian beretorika menjadi alat resistensi. Ia menyatakan keteguhan sumpah, mengungkit penghinaan, dan menolak narasi belas kasihan. Justru dari hal tersebut, muncul konfigurasi baru dari perempuan yang tidak menunggu diselamatkan, melainkan mendorong laki-laki untuk menepati sumpah mereka, bahkan ketika ia menyebut nama Shikandi—seorang tokoh yang secara mitologis mengalami transisi gender. Drupadi seolah menyentuh kemungkinan bahwa keberanian dan perlawanan bukanlah hak eksklusif satu jenis kelamin. Di sinilah, strategi monolog dramatik berfungsi sebagai alat konseptual untuk memperluas makna maskulinitas, hingga dapat dijalani dan ditunjukkan oleh tokoh perempuan.
SGA menyusun ulang peta gender dalam dunia epik. Maskulinitas tidak lagi terletak pada tubuh lelaki atau gelar “ksatria”, melainkan pada tindakan dan keberanian moral untuk menyuarakan keadilan. Sehingga melalui monolog dramatik yang tegang dan menyayat, SGA menaruh maskulinitas itu tepat di mulut Drupadi, sebagai perempuan yang tak lagi menunggu dibela, tapi siap menuntut darah dan harga diri.
Dalam monolog dramatik yang menggelegar itu, Drupadi menyeret pembaca pada medan perang yang lebih dalam: perang melawan diam, perang melawan ‘penjinakan perempuan’, serta perang melawan sistem nilai yang merendahkan perempuan seakan hanya pelengkap bagi “keperkasaan” laki-laki. Di sinilah suara Drupadi merebut posisi simbolik yang selama ini disebut Connell sebagai hegemonic masculinity—posisi dominan yang dilekatkan pada laki-laki, yang ditandai oleh keberanian, otoritas, kuasa untuk menentukan, dan hak untuk membungkam. Lewat strategi monolog dramatik, SGA justru menaruh ‘hegemonik’ itu di mulut seorang perempuan yang telah terlalu lama dikorbankan oleh nama besar Pandawa.
Membaca monolog dramatik ini lebih sebagai upaya sadar dari SGA untuk membongkar struktur gender epik Mahabharata. Ia menulis ulang panggung kuasa dengan menjadikan Drupadi sebagai satu-satunya suara yang penuh kemarahan, retoris, tegas, dan memantik ketegangan dalam ruang balairung. SGA memfokuskan sorotan kepada satu pertanyaan besar: “Siapa sebenarnya yang paling gagah?” Dan ‘gagah’ atau ‘berkuasa’ adalah posisi dalam relasi sosial yang bisa berpindah dan bisa diperebutkan. Melalui monolog yang lirih dan menggugah, SGA menghadirkan suara Drupadi yang bening dan tegas. Lalu di sana, topeng maskulinitas epik itu seketika runtuh.[]
Referensi:
Abrams, M.H., 1999. A Glossary of Literary Terms. 7th ed. Fort Worth: Harcourt Brace.
Ajidarma, Seno G. 2017. Drupadi Perempuan Poliandris. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Baldick, C., 2015. The Oxford Dictionary of Literary Terms. 4th ed. Oxford: Oxford University Press.
Beynon, J., 2002. Masculinities and Culture. Buckingham: Open University Press.
Connell, R.W. 1995. Masculinities, Sydney: Allen & Unwin
Connell, R. (1997). Gender Politics for Men. International Journal of Sociology and Social Policy. Vol. 17 No. 1/2. hlm. 62—77.
Faruk. 2020. Metode Penelitian Sastra Cetakan Kelima. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
Langbaum, R., 1957. The Poetry of Experience: The Dramatic Monologue in Modern Literary Tradition. Berkeley: University of California Press.
Penulis: Via Ajeng, suka membaca, menulis, mendengarkan musik, nyanyi, dan kontemplasi. Kini tinggal di Yogyakarta. Dapat dihubungi melalui instagram viaajeng_27 atau melalui surel viaajeng.24@gmail.com
 Ketiketik.com Mengetik dan Menalar Perubahan
Ketiketik.com Mengetik dan Menalar Perubahan