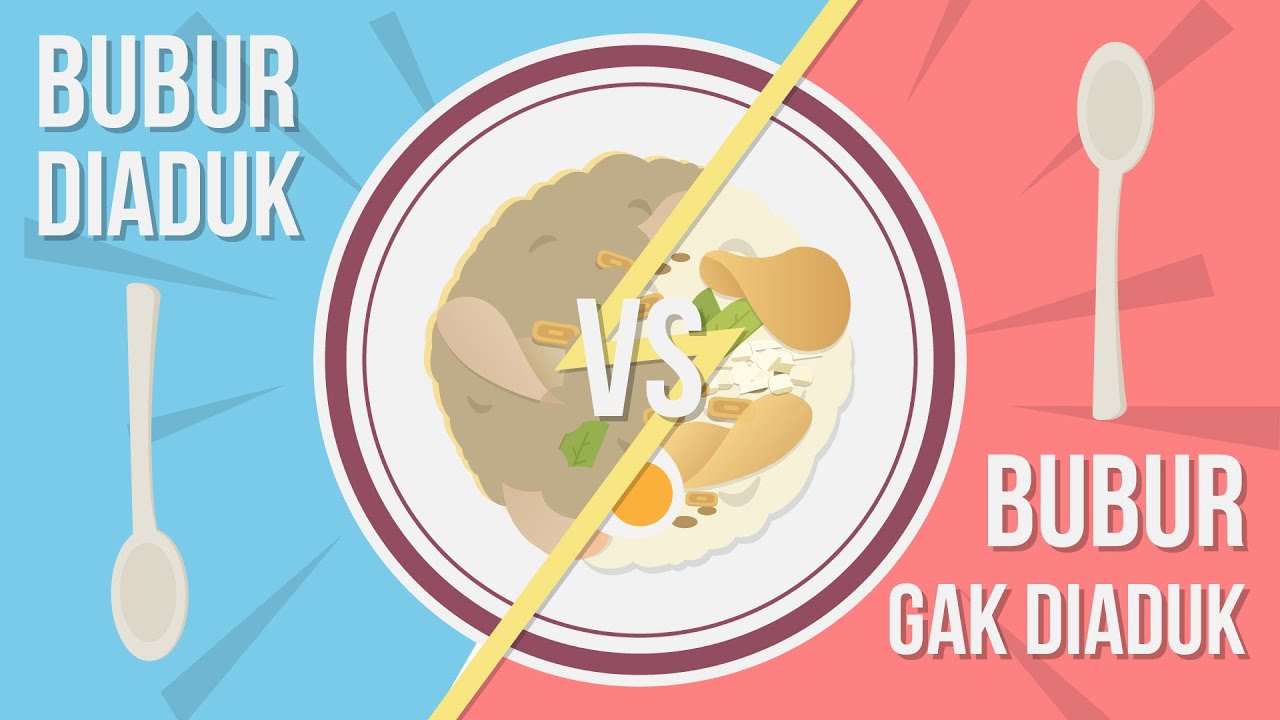
Meski saya memegang prinsip yang cukup optimis dalam melihat hidup, jujur ada satu karakteristik nihilis yang cukup saya sepakati. Saya mengamini bahwa memang ada hal-hal di dalam hidup ini yang nirmakna, tidak memiliki makna, tidak penting, atau less priority kalau kata kaum praktis. Mari saya jabarkan konteksnya.
Hal-hal nirmakna yang saya bicarakan berkenaan dengan individu dan glorifikasi atas atribut yang melekat di dirinya. Menurut saya, tidak penting untuk menilai kualitas individu dari hal-hal yang bisa dipasanglepas atau sekadar memanjakan mata. Apalagi atribut ini bersifat subjektif dan tidak memiliki pengukuran variabel yang jelas. Memang terdengar sedikit positivis, namun bukankah itu adalah karakteristik era pasca modern yang konon katanya serba ilmiah?
Saya jumpai beberapa orang yang menilai musik Brit Pop sebagai selera musik yang keren sementara musik pop melayu Indonesia norak. Di internet, ada terminologi-terminologi baru seperti The Nuruls dan The Nopals untuk mengidentifikasi sekelompok remaja dengan kebiasaan membeli jajanan kaki lima dan tampil dengan outfit harga terjangkau.
Tak sedikit pecinta Vespa menalak pengguna Mio karbu sebagai suatu anomali. Pemisalan paling sederhana, misalnya seorang pecinta bubur diaduk menuding pecinta bubur tidak diaduk telah menganut paham yang salah. Jika ditelaah, generasi judgemental ini mengidap suatu penyakit mental masa kini yang bernama kompleks superioritas —perasaan merasa lebih unggul daripada orang lain.
Kompleks superioritas didefinisikan sebagai patologi yang pada kondisi mental seseorang yang merasa lebih unggul daripada individu atau lingkup masyarakat tertentu. Kondisi ini sangat memungkinkan menimbulkan tindakan-tindakan diskriminasi lainnya. Seseorang yang mengidap kompleks superioritas biasanya melakukan segregasi atau pemisahan dengan kelompok lain yang ia rasa tidak setara atau lebih rendah daripadanya. Dalam lingkup global, kompleks superioritas ini menjadi akar dari tindakan rasisme dan supremasi kelompok tertentu.
Banyak sejarah-sejarah besar terjadi berakar pada satu premis yang sama, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mengidap kompleks superioritas memiliki kekuasaan. Otoritas ini memungkinkan individu atau kelompok ini melakukan hal-hal dehumanis kepada kelompok yang berseberangan dari mereka. Holocaust berangkat dari ras arya yang merasa lebih unggul daripada yahudi. Genosida –yang meski masih tidak diakui sebagai genosida oleh yang kelompok mayoritas dan berkepentingan– komunis 65 berakar dari sentimentil ideologi yang dianut sayap kanan kepada ideologi sayap kiri.
Anggaplah kecil kemungkinan akan ada pembantaian terhadap kaum bubur tidak diaduk oleh kaum bubur diaduk, bagaimana dengan tindakan dehumanis skala kecil di lingkup domestik? Tindakan perundungan acapkali berakar pada segregasi kelompok mayoritas terhadap satu individu yang tidak memenuhi standar absurd yang mereka tetapkan. Perundungan menjadi bukti kecil bagaimana kompleks superioritas memproyeksikan primordialisme, narsistik, dan egosentris si pelaku.
Kembali ke premis yang saya bawakan di awal. Apakah penting terlahir dengan kulit putih? Apakah ras arya benar-benar lebih unggul? Apakah menghapal album The Beatles membuat kita lebih mulia daripada pecinta Deni Caknan? Apakah berpegang teguh pada kepercayaan bumi berbentuk donat membuat seseorang lebih pintar daripada yang percaya bumi ini berbentuk heksagonal? Kali ini saya sepakat dengan Mersault dalam The Stranger yang ditulis Albert Camus. Segala hal yang kita temui sehari-hari acapkali tidak penting –tak bermakna. Setiap hari adalah hari baru dan kebenaran mereduksi dirinya sendiri. Kebenaran mana lagi yang harus dipertahankan sebagai yang hakiki?
Berbicara kebenaran membuat saya terpikir penyakit masyarakat masa kini –tak lain tak bukan perang kebenaran. Menunjuk siapa yang benar siapa yang salah juga tidak lebih penting sebab kita telah menapaki area abu-abu dunia pasca modernisme yang menitikberatkan kebenaran sebagai sesuatu yang terlampau subjektif. Kita pahami bahwa subjektivitas sangatlah sentimental, hendaknya disimpan sendiri. Analogikan dengan Being dan Nothingness.
Apakah being selalu berupa sesuatu yang ada? Apakah nothingness serta merta perkara ketiadaan. Nyatanya mereka berkelindan membentuk simbiosis yang saling mengikat. Ketiadaan ada karena ada. Vice versa, ada kehilangan hakikat jika tak mengenal ketiadaan. Manakah yang lebih unggul, kaum empiris yang berpegang teguh pada pengalaman inderawi atau kaum idealis yang tenggelam dalam dunia idea? Tidak ada yang lebih unggul, semua memiliki corak berpikir di masing-masing frame.
Begitu pula argumen ini bermula. Ini adalah kritik terhadap suatu selisih yang acapkali tak penting untuk diperpanjang apalagi sampai melahirkan benih kebencian dan dalam versi lebih parahnya, peperangan. Coba bayangkan jika Hitler dan Netanyahu paham Bhinneka Tunggal Ika atau nilai-nilai heterogen. Bayangkan jika semua orang tahu teori klasik kapitalisme bahwa orang kaya adalah mereka yang menguasai alat produksi bukannya konsumtif. Hal-hal utopis yang terlalu indah untuk terjadi ini mungkin juga hal-hal nirmakna. Mungkin dan mungkin lagi dunia yang karut-marut dengan kemungkinan muskil maupun boleh jadi terjadi adalah hal-hal nirmakna pula.
–
Windy Shelia Azhar merupakan penulis berdarah Melayu Bangka yang saat ini bermukim di Bali. Ia pernah berkuliah di jurusan Sastra Inggris lalu menempuh pendidikan Ilmu Komunikasi. Cerpen dan esai yang ia tulis berkutat dengan isu gender, lingkungan, dan kebahasaan telah tersebar di berbagai medium. Ia juga bagian dari Kebun Kata, komunitas literasi berbasis di Bangka Belitung. Jalin korespondensi dengannya via pos el: tuliswindy@gmail.com atau baca tulisannya di medium.com/
 Ketiketik.com Mengetik dan Menalar Perubahan
Ketiketik.com Mengetik dan Menalar Perubahan
