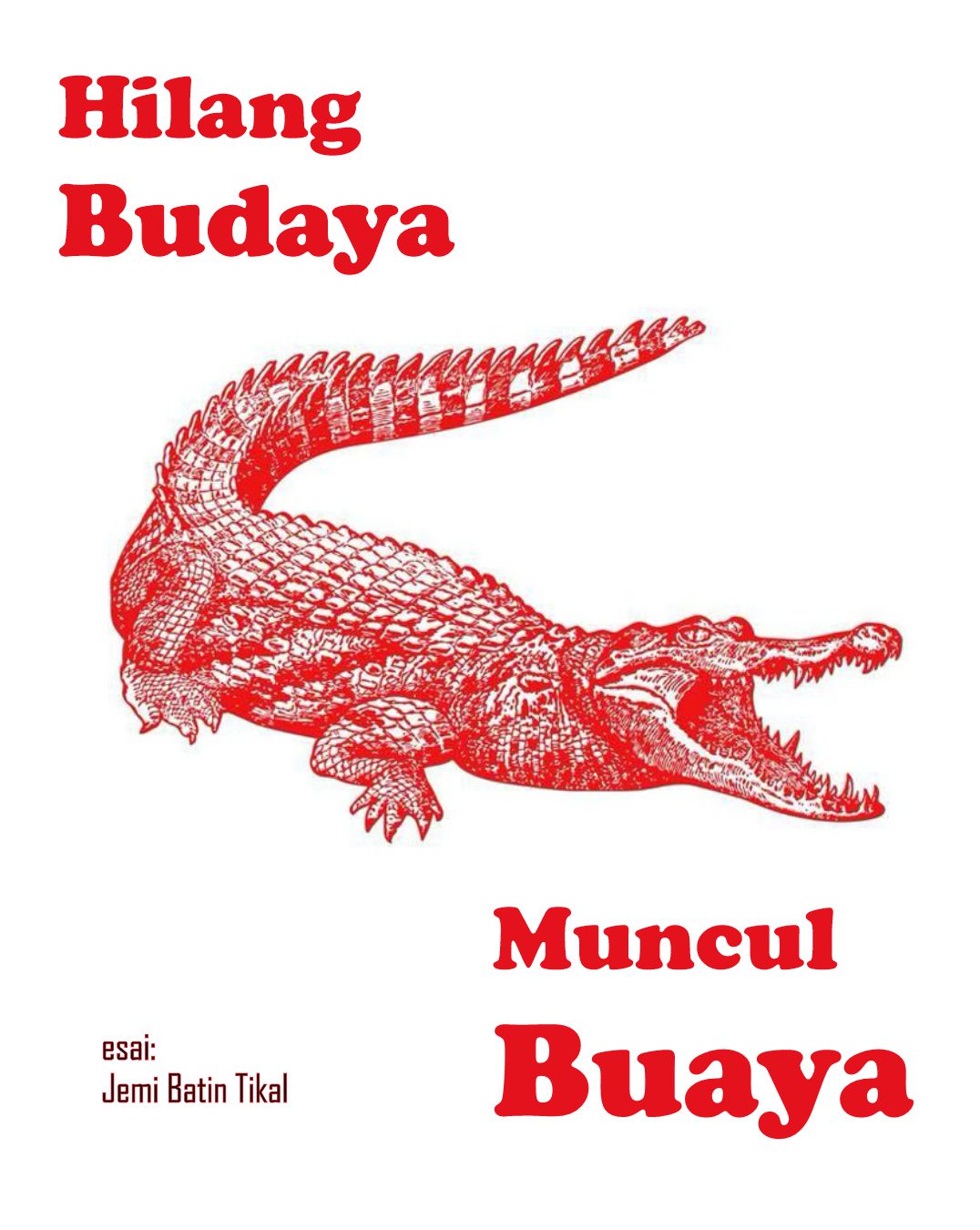
Kurun 2015 hingga 2016, sebut saja Bujang mendapati banyak sekali kasus konflik antara manusia & buaya. Waktu itu warga desanya ada yang ditabrak/dicakar buaya ketika sedang berenang, yang menyebabkan dada si korban tercabik-cabik. Sebelum kejadian itu warga desa sebelah juga diserang buaya, salah satu tangannya putus. Ia selamat. Kemudian diadakanlah upaya mencari buaya yang didakwa sebagai pelaku. Pencarian ini melibatkan pawang dari sebuah desa yang jauh. Menurut angin yang beredar, biaya pencarian ini menghabiskan uang puluhan juta rupiah.
Berapa hari kemudian, buaya terdakwa terpancing, sebagai pesakitan, ia diikat dan dipamerkan di balai desa. Tokoh Kita pun berangkat bersama pamannya ke desa sebelah yang hanya berjarak 15 menit untuk melihat sang buaya. Reptil tersebut kira-kira sepanjang 4 m, tak berdaya. Esoknya perut buaya ini dibelah untuk mencari tangan warga tadi. Buaya ini mati & dikuburkan di ujung kampung. Selepas itu, ada angin lain yang berembus yang mengatakan bahwa buaya yang perutnya dibelah bukanlah buaya yang menggigit warga desa sebelah.
Akhir 2016, Bujang berangkat ke suatu daerah. Pada abad 18 hingga 19, di daerah ini terdapat acara rampogan, yaitu mengadu macan (harimau) dengan kerbau, babi, atau dengan manusia. Namun adu dengan manusia sangat tidak kesatria. Macan di lepas di alun-alun yang telah dikelilingi ratusan bahkan ribuan manusia dengan bersenjatakan keris atau tombak. Macan yang hendak lari melewati pagar manusia dihujani dengan mata tombak. Konon, acara ini merupakan salah satu penyebab kepunahan harimau di Jawa.
Satu windu sejak kepergian Bujang, pada awal 2024 muncul lagi berita, tangan seorang warga dari desanya putus setelah diterkam buaya ketika sedang mencari ikan di sungai. Selang tiga bulan, pada akhir Maret warga lain dari desanya disambar buaya ketika sedang di atas sampan. Setelah dua pekan pencarian, tak kunjung ditemukan.
Konflik manusia dengan hewan merupakan masalah yang belum terselesaikan di daerah manapun. Di Sumatra, manusia berkonflik dengan gajah, harimau, atau orang utan. Di Kalimantan, orang utan versus orang kota. Konflik semacam ini bagai pisau bermata dua, pada satu sisi menimbulkan kerugian material dengan hilangnya mata pencaharian masyarakat. Namun di sisi lain, mengancam keberlangsungan hidup satwa, serta pada tingkatan terparah dapat menimbulkan korban jiwa.
Rusaknya habitat merupakan penyebab utama konflik, selain itu kearifan lokal masyarakat menghormati satwa juga sudah mulai luntur bahkan hilang sama sekali. Orang Melayu Bangka, terutama di daerah asal Bujang, jika ke sungai & bertemu buaya, mereka tidak menyebutnya dengan “buaya”, tapi “abok atau nek” yang artinya “kakek atau nenek”. Orang Jawa pada masa lampu juga menghargai macan dengan memanggilnya “si mbah”.
Masyarakat Nagarawangi juga memiliki panggilan penghormatan untuk harimau atau maung di Gunung Beser. Penyebutan maung disamarkan dengan menyebutnya sebagai urang leuweung (orang hutan). Kera besar yang terdapat di Sumatra & Kalimantan juga disebut dengan embel-embel nama depan “orang” dan “utan” nama belakangnya. Masyarakat kita dulu tentu tidak asal menyebut hewan dengan label “orang”, hal ini tentu merupakan wujud saling menghormati & menjaga keseimbangan alam & mahkluk hidup lain.
Selain orang Jawa, orang Minangkabau juga jarang menyebut harimau secara verbal. Melainkan sering disebut “inyiak” atau “inyiak balang”, yang bisa berarti kakek atau bapak. Sedangkan di Papua, bagi orang Marind, hutan merupakan sistem kehidupan yang keberadaannya melingkupi tanaman & hewan-hewan, juga manusia, posisi ketiganya dianggap setara & saling memiliki keterikatan-keterkaitan. Orang Marind menganggap hutan sebagai “keluarga” mereka yang merepresentasikan hubungan & berasal dari keturunan roh leluhur yang dema (sama).
Pada masa lalu maupun sekarang ini di Bangka, buaya & hewan lain makin terus terpojok akibat pembukaan, perambahan, pembalakan hutan untuk terutama pertambangan timah. Banyak anak-anak atau cabang-cabang sungai yang bergeser atau mati. Hal ini menyebabkan habitat buaya terusik, sumber makanan alami seperti kera, kancil, rusa, kijang, dll juga semakin menipis. Akibatnya, buaya semakin sulit mencari mangsa alami & kita tahu akhirnya seperti apa.
Ironinya, seperti disampaikan di awal, orang Melayu Bangka sebenarnya sangat akrab & punya hubungan baik, juga menganggap buaya bagian dari keluarga dengan sebutan “abok”, “nek”, atau “atuk”. Hal ini juga dapat ditemukan dalam kisah yang ditulis salah satu penulis kenamaan asal Bangka, Linda Christanty.
“telur-telur yang telah didoakan dan dimasukkan dalam mulut buaya tadi untuk mengobati anak-anak kecil yang demam dalam keluarga mereka. Nenek Buyut perempuan tersebut dulu melahirkan anak kembar, manusia dan buaya. Saudara Mak Nga ini keturunan dari pihak manusia, sehingga Buntung terhitung kakeknya.
Dalam kisah-kisah Melayu, manusia yang melahirkan buaya sama sekali bukan hal aneh. Pak Kok, mertua sepupu saya, Bang Heri, secara rutin mengunjungi saudara kembarnya yang juga seekor buaya. Pak Kok tinggal dalam sungai selama dua minggu.” Tulis Linda di esai berjudul Syarifah Maryam Alkaf dan Si Buntung dalam buku Para Raja dan Revolusi (2016).
Dari jarak 1.300 kilometer di jantung Jawa, Bujang hari-hari ini begitu akrab dengan berita konflik manusia vs buaya. Hal itu memantik ingatan bertahun silam. Kakek si Bujang konon adalah penjaga (kuncen) sebuah sungai di dekat desanya. Oleh sebab itu, istri & anak si kakek sering bersinggungan tak sengaja dengan buaya, semisal berenang dengan jarak tak jauh tanpa pernah diserang buaya.
Pada musim kemarau, si kakek sering mengingatkan keluarga & anak turunannya agar tak menuba (aktivitas mencari ikan dengan menabur akar tuba, agar ikan pusing & timbul ke permukaan) di sungai. Pantangan ini hanya berlaku untuk keluarganya, bagi orang lain tetap boleh. Namun setelah mengenal bahan kimia, beberapa warga pada musim kemarau tak menggunakan akar tuba lagi, melainkan racun Potas. Bahan kimia ini tak hanya membuat ikan pusing, tapi mati, termasuk anakan ikan yang masih kecil.
Tiap musim kemarau melanda, biasanya terjadi konflik antarhewan dengan manusia. Media kemudian memberitakan dengan judul kurang lebih seperti ini
“hewan liar masuk ke perkampungan, merusak tanaman & menyerang ternak warga”.
Bujang sejatinya kurang setuju dengan anggapan demikian & bertanya-tanya, bukankah manusia yang makin hari makin masuk ke hutan? Membuat perkampungan makin dekat dengan habibat hewan? Merambah hutan tanpa ampun & tidak melakukan reboisasi kembali? Manusia tak lagi menganggap hutan, tanaman, hewan sebagai bagian dari keseimbangan alam? Bukan buaya yang tak bisa kita percaya, tapi manusia? Manusia menambang timah di daratan bahkan hingga mengeruk lautan. Lalu hari-hari ini, banyak berita bermunculan, hasil tambang timah tersebut digarong para maling, kemudian memecahkan rekor korupsi & kerugian terbesar, ratusan triliun?
Penulis: Jemi Batin Tikal, belajar menulis puisi, cerita pendek, esai, & lirik lagu. Mengisi harinya dengan membaca, buruh di penerbitan, & mengeditori buku. Kumpulan puisi Yang Tidak Mereka Bicarakan Ketika Mereka Berbicara tentang Cinta (Oktober, 2023) adalah buku puisi pertamanya. Ia memiliki ketertarikan pada isu lingkungan, sejarah & politik. Ia sedang mengerjakan buku puisi kedua. Ia bisa dicubit via akun Instagram @jemibatintikal
 Ketiketik.com Mengetik dan Menalar Perubahan
Ketiketik.com Mengetik dan Menalar Perubahan
