Nilai kehidupan dapat direfleksikan dalam karya sastra. Nilai tersebut terejawantahkan baik berdasarkan pengalaman, pengamatan, pemikiran, ataupun refleksi dari penulisnya. Nilai itu beragam, mengingat setiap penulis memiliki keinginan untuk menampilkan corak atau topik tertentu dalam karya mereka; mulai dari hal-hal besar tentang ihwal negara atau pemerintah sampai hal-ihwal kedirian atau topik-topik remeh yang kerap dilupakan. Dalam hal ini, terdapat anggapan bahwa karya yang tak menghadirkan hal-hal besar tak sesignifikan karya yang berbicara topik tersebut. Topik-topik keibuan, domestik, dan hal-hal yang berkisar di sekitarnya masih menjadi ranah yang jarang disentuh banyak penulis.
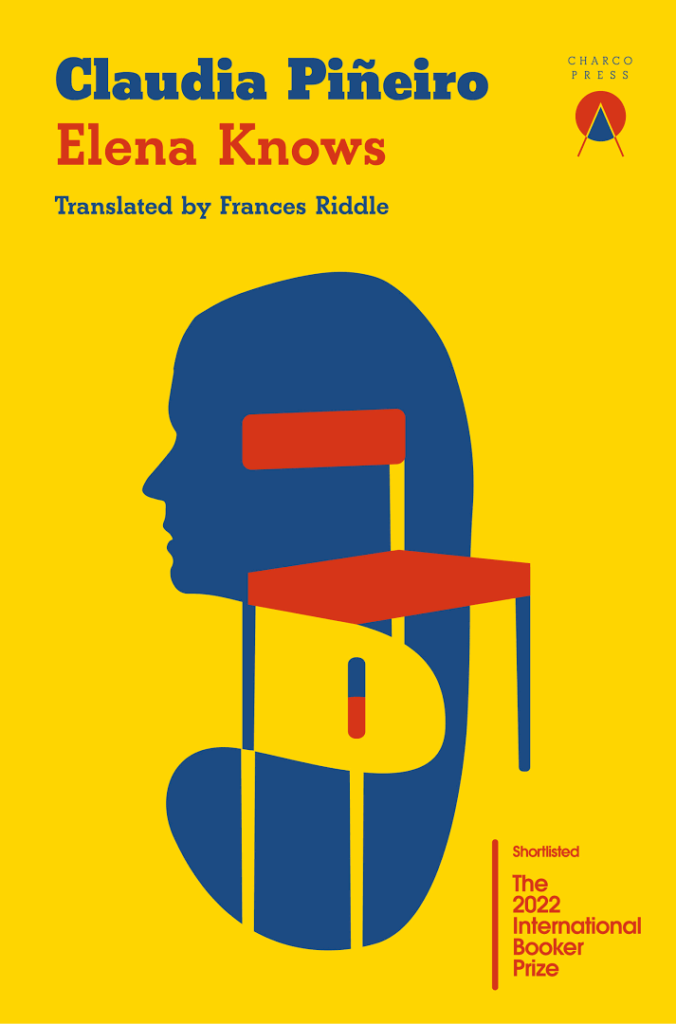
Padahal, esensi topik itu tak kalah pentingnya, sebab pembahasan mengenainya dapat membuka beragam dialog dengan perspektif baru di dalamnya. Namun selalu ada pengecualiaan, terdapat beberapa penulis yang justru memfokuskan diri pada topik-topik yang diluputkan tersebut. Di ranah inilah, kita patut memperhitungkan nama Claudia Piñeiro yang berkiprah di jagat sastra Amerika Latin kontemporer. Nama itu mencuat di ranah global setelah novel debutnya, Elena Knows (Terjemahan Frances Riddle; Charco Press, 2021), menampilkan wajah baru kesusastraan Amerika Latin dengan menghadirkan topik keibuan yang segar dan berani.
Piñeiro seorang pencerita yang tak muluk –ia tak bertendensi berbicara hal besar atau rumit. Terlepas sekian kritik tajam terhadap masyarakat gereja di Brazil yang menyusup di dalam cerita, utamanya, ia ingin bercerita tentang ibu, kehilangan, dan pemaknaan ulang atas relasi ibu dan anak. Cerita berkisar tentang hubungan Elena dan anaknya, Rita. Suatu hari, Rita ditemukan gantung diri di menara lonceng gereja. Orang-orang mengatakan ia bunuh diri. Polisi pun menyatakan hal yang serupa. Tapi tidak dengan Elena, ia yakin Rita tak bunuh diri, melainkan dibunuh. Lalu atas dasar hal apa yang membuatnya yakin?
Pertama, Rita meninggal kala hujan lebat penuh sambaran petir; dan Elena tahu pasti, Rita takut kepada petir, sehingga ia tak mungkin pergi ke menara lonceng gereja di tengah hujan dan menggantung dirinya. Kedua, Elena sebagai seorang ibu pasti mengetahui segala hal tentang anaknya. Seperti yang dituturkan Piñeiro: ‘Tak ada orang lain yang mengenal dan tahu banyak hal tentang anak perempuannya sebaik dia, pikir Elena, sebab dia adalah ibunya [….] Keibuan, pikir Elena, dilandasi oleh hal-hal tertentu, seorang ibu mengenal anaknya, seorang ibu tahu anaknya, seorang ibu mencintai anaknya.’ (hal. 49)
Pemaknaan yang tampil dari narasi di atas jelas tentang seorang ibu yang tahu segala hal ihwal anaknya. Itu pun yang diyakini oleh Elena, serta yang menjadi landasan penamaan judul novel ini “Elena Knows“. Tapi, novel ini ingin menyelisik hal lain: paradoks dari kalimat tersebut. Apakah Elena benar-benar mengetahui segalanya? Bagaimana dengan hal yang tak diketahui oleh Elena? Dua pertanyaan ini menggerakkan alur cerita seiring upaya Elena yang ingin menguak misteri kematian anaknya.
Pertanyaan itu terus membayangi perjalanannya, mengingat semakin Elena berjalan, dan semakin dalam Elena menggali, ia justru menemukan hal-hal yang tak diketahui tentang anaknya, kehidupannya, dan hal itu mengantarkannya ke ruang pemaknaan ulang atas diri dan relasi keduanya sebagai ibu-anak. Pemaknaan itu tentu hal yang tak mudah dan menyesakkan. Elena menguak tentang trauma, hubungan tak sehat, dan rasa sakit yang selama ini tersembunyi di bawah atap rumah yang mereka huni. Namun melalui semua itu, ruang kontemplasi terbuka di benaknya seiring semakin jauh pembaca menyelami kisah perjalanannya.
Cinta Seorang Ibu dan Kebimbangannya
Jika Elena Knows berbicara mengenai ruang pemahaman ibu dan anak yang rumpang dan dimaknai ulang sejak tragedi kematian anaknya, Rita; ihwal keibuan yang terkandung dalam novel Piñeiro terbaru, A Little Luck (Terjemahan Frances Riddle; Charco Press, 2023), berkisar ke hal yang lebih kompleks lagi. Novel ini dibuka dengan adegan seorang perempuan dalam perjalanan ke Temperley, kota di Brazil yang sudah dua puluh tahun ia tinggalkan. Perjalanan yang dilakukan memang perjalanan dinas, mengingat tujuannya pergi ke sekolah swasta di kota itu untuk meninjau kelayakan mereka berafiliasi dengan lembaga pendidikan tempatnya bekerja di Boston; tapi itu bukan hanya perjalanan resmi, mengingat kota itu menyimpan cerita tersendiri mengenai ia dan masa lalu yang tak ingin diingat, keputusan berat yang mesti diambil, dan bayangan kesalahannya sebagai seorang ibu.
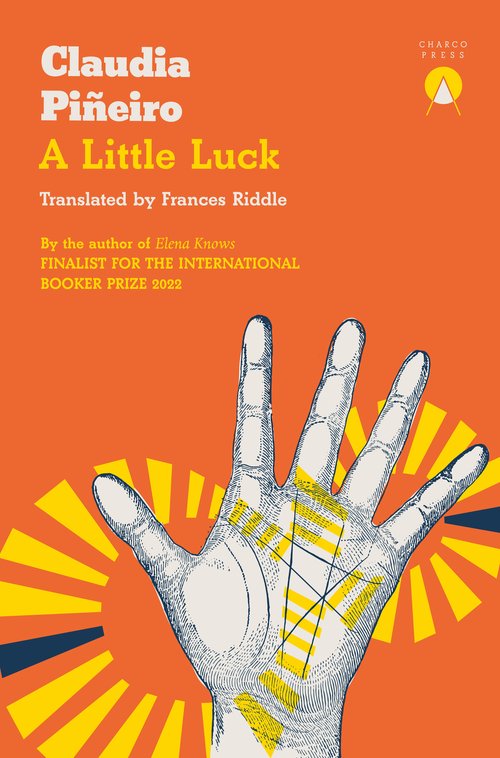
Kita masih menemukan kekhasan Piñeiro dalam novel ini. Ia merajut alur dengan pelan, menyingkap lapis demi lapis misteri, dan membiarkan pembaca mendapat jawab atas sekian pertanyaan yang muncul sepanjang cerita. Begitu pula terhadap kisah perempuan bernama Mary Lohan ini. Sekembalinya dari sana, Mary mesti siap menghadapi tiap bagian kota yang sedemikian dikenalinya. Dulu, ia tinggal di kota tersebut sebelum pergi tanpa tujuan dan berakhir di Boston. Dulu, ia punya keluarga dengan satu orang anak. Tapi dulu, satu tragedi mengubah segalanya: suatu siang, mobil yang dikendarainya bersama sang anak dan teman anaknya terlindas kereta saat melewati palang pintu yang rusak. Mobil itu macet tepat sebelum kereta datang. Ia dan anaknya berhasil keluar, tapi tidak dengan teman anaknya; anak itu meninggal di tempat, dan Mary merasa bersalah luar biasa.
Rasa bersalah itu semakin diperparah dengan sedikitnya dukungan yang menguatkannya. Sebab hal itu bukan salah Mary sepenuhnya, nasib buruklah yang mengantarkannya ke titik itu. Situasi makin tak mengenakkan pun muncul saat anaknya ikut terkena getah dari peristiwa itu. Ia dikucilkan di sekolah dan para ibu pun membicarakannya. Situasi keluarganya juga menegang saat Mary berinisiatif pindah tapi suaminya enggan. Keputusan berat pun diambil, bahwa anaknya akan baik-baik saja dan beroleh hari seperti biasa kalau ia tak di sana. Dengan berat hati, Mary pun pergi.
Dua puluh tahun berlalu dan ia kembali dengan jati diri baru. Mary Lohan bukan nama aslinya, Lohan diambil dari nama lelaki yang menemaninya di Boston; kini, ia pun pirang, mengenakan lensa kontak, dan punya identitas baru. Seharusnya, perkara berkunjung ke kota itu tak perlu serunyam ini rasanya. Tapi Mary menghadapi kenyataan baru, anak lelakinya yang dulu ditinggalkan, kini menjadi guru di sekolah yang dikunjunginya. Pertemuan keduanya pun menjadi pintu dari dibukanya dialog atas masa lalu, hal yang tak selesai, dan pemaknaan dalam hubungan keduanya. Bagaimana Mary menghadapi semua itu?
Lagi, nilai keibuan mengental dalam cerita ini. Nilai itu utamanya ada dalam keraguan layak atau tidaknya; pantas atau tidaknya; dan siap atau tidaknya seseorang akan atau ingin menjadi seorang ibu –yang baik. Mary sempat merasakan keraguan itu: “Tapi, terlepas dari mencintai anak itu, apakah aku ingin menjadi seorang ibu? Adakah seseorang mampu memahamiku, mampu mengerti perasaan ambivalen itu: mencintai anakmu, mencintainya sedemikian dalam, sembari meragukan kedirianmu menjadi seorang ibu? Dan pertanyaan itu diikuti pertanyaan lainnya: bahkan, apakah aku layak menjadi seorang ibu? Bisakah aku menanganinya?” (hal. 95) Pertanyaan itu muncul diikuti beragam keraguan dan kebimbangan yang membayanginya sekian tahun. Perjalanannya kembali ke sana pun menjadi upaya memaknai ulang semua hal itu.
Dengan cara mereka masing-masing, pemaknaan dan dialog itu dilakukan. Kendati mereka menghadapi situasi yang berbeda, tapi bisa dikatakan, nilai-nilai keibuan yang dipertanyakan dan dimaknai ulang dalam kedua prosa (baca: novel) Claudia Piñeiro itu dengan gamblang membuka ruang dialog yang beragam dan mendobrak sekat ketabuan. Dialog itu tak hanya dialami oleh kedua karakter utamanya, yang mempertanyakan kedirian sebagai ibu yang tahu segalanya sekaligus tak mengetahui apa-apa, juga yang memaknai ulang peristiwa masa lalu, cinta dan kelayakannya sebagai seorang ibu, serta mengupayakan pertanggungjawaban dan cara berdamai atas tindakannya. Lebih dari itu, dialog itu mengajak pembaca melihat sekeliling untuk menyadari bahwa ihwal keibuan adalah hal yang sedemikian kompleks. Dialog yang tercipta mesti memasuki ruang paling privat yang selama ini mungkin terkungkung dengan kekakuan dan ketabuan yang ada di masyarakat. Dialog itu perlu hadir sekalipun sesederhana pertanyaan: Apa yang kita ketahui untuk menjadi ibu? Apakah kita layak? Hal apa saja yang mesti disiapkan? Dan apa yang membuat kita menjadi seorang ibu yang baik?
Penulis Wahid Kurniawan, peminat sastra, alumnus Sastra Inggris di Universitas Teknokrat Indonesia
Pemeriksa Aksara: Windy Shelia Azhar
 Ketiketik.com Mengetik dan Menalar Perubahan
Ketiketik.com Mengetik dan Menalar Perubahan
